24 Mei Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia, Menembus Kabut Stigma, Menggenggam Harapan
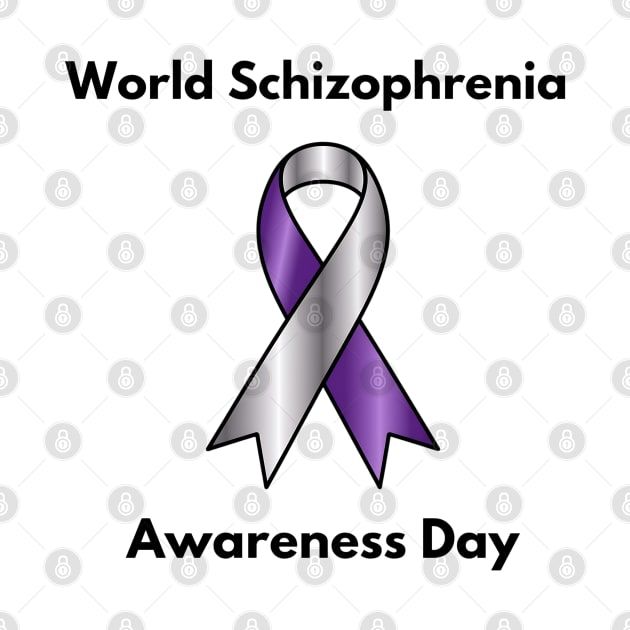
Hari Skizofrenia: Hapus Stigma!-pinterest-
Gejala skizofrenia biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar: gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif bukan berarti “baik”, melainkan mengacu pada penambahan pengalaman abnormal, seperti delusi dan halusinasi. Penderita bisa merasa sedang diawasi oleh pemerintah, percaya dirinya nabi, atau mendengar suara-suara yang memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Ini bisa sangat mengganggu dan menakutkan, bahkan membuat penderita merespons terhadap sesuatu yang tidak nyata.
Sebaliknya, gejala negatif mencerminkan berkurangnya fungsi-fungsi normal. Misalnya, penderita jadi tidak mampu mengekspresikan emosi, tidak menikmati aktivitas yang dulu disukai, atau bahkan tidak mampu berbicara lancar. Gejala ini membuat penderita tampak “kosong” secara emosional dan cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Yang menyulitkan, gejala negatif sering kali lebih tahan lama dan tidak terlalu responsif terhadap obat dibanding gejala positif. Karena itu, pemulihan skizofrenia tak hanya soal menghilangkan halusinasi, tetapi juga mengembalikan fungsi sosial dan emosi seseorang.
5. Usia Munculnya: Tak Terduga Tapi Bisa Diprediksi
Skizofrenia paling sering muncul pada usia remaja akhir hingga awal dewasa, antara usia 16 hingga 30 tahun. Pada pria, gejala umumnya mulai tampak di akhir masa remaja, sedangkan pada wanita biasanya muncul sedikit lebih lambat. Masa awal ini sangat penting karena sering kali gejalanya belum begitu jelas—perubahan perilaku, mulai menarik diri, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Fase ini disebut fase prodromal, dan bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Sayangnya, banyak keluarga atau tenaga pendidik tidak mengenali tanda-tanda awal ini. Perubahan perilaku kerap dianggap sebagai kenakalan remaja atau fase pemberontakan. Akibatnya, diagnosis sering terlambat dan penderita baru mendapat pengobatan setelah mengalami episode psikotik penuh.
6. Perjalanan Penyakit: Kronis, Tapi Bisa Diatur
Skizofrenia memang merupakan kondisi kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang, tapi bukan berarti tak bisa dikelola. Banyak penyintas yang mampu kembali berfungsi di masyarakat, bekerja, berkeluarga, bahkan kuliah. Kuncinya adalah pengobatan rutin, dukungan sosial, serta lingkungan yang mendukung. Skizofrenia bukan seperti pilek yang bisa sembuh total, melainkan seperti diabetes—perlu pemantauan dan pengelolaan seumur hidup.
Dalam jurnal JAMA Psychiatry tahun 2023 disebutkan bahwa hingga 60% penderita skizofrenia bisa mencapai remisi dengan pendekatan holistik: obat-obatan, terapi psikologis, dan keterlibatan keluarga. Remisi bukan berarti sembuh total, melainkan kondisi di mana gejala minimal dan fungsi sosial membaik. Penderita bisa kembali ke bangku kuliah, bekerja, bahkan memiliki keluarga, asal memiliki sistem pendukung yang kuat dan disiplin menjalani terapi.
7. Terapi dan Pengobatan: Lebih dari Sekadar Obat
Pengobatan utama skizofrenia adalah obat antipsikotik, yang bekerja mengatur kadar neurotransmiter seperti dopamin di otak. Obat generasi pertama (misalnya haloperidol) dan generasi kedua (seperti olanzapine atau risperidone) efektif dalam mengurangi gejala halusinasi dan delusi. Namun, pengobatan tidak berhenti di situ. Efek samping dari obat seperti tremor, kenaikan berat badan, atau kelesuan emosional membuat pentingnya evaluasi berkala oleh psikiater.
Selain obat, penderita skizofrenia juga membutuhkan terapi psikososial seperti terapi kognitif-perilaku (CBT), terapi okupasi, pelatihan keterampilan sosial, dan dukungan keluarga.
8. Stigma dan Miskonsepsi: Musuh Terbesar Bukan Gejala, Tapi Masyarakat
Salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan skizofrenia adalah stigma yang mengelilinginya. Masyarakat sering menganggap orang dengan skizofrenia berbahaya, tidak bisa sembuh, atau bahkan “kerasukan”. Akibatnya, banyak penderita yang disembunyikan oleh keluarga, tidak dibawa berobat, atau lebih parah—dipasung. Padahal, studi dari The Lancet Psychiatry menunjukkan bahwa dukungan sosial yang buruk meningkatkan risiko kambuh hingga dua kali lipat.
Penyintas skizofrenia juga kerap mengalami diskriminasi di tempat kerja, sekolah, hingga rumah ibadah. Hal ini membuat mereka enggan untuk terbuka dan mencari bantuan. Edukasi publik yang benar, pelatihan bagi petugas layanan publik, dan kampanye kesadaran lewat media sangat diperlukan untuk memutus lingkaran stigma ini. Kita perlu berhenti memperlakukan skizofrenia sebagai aib, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari keberagaman kondisi manusia yang layak dimanusiakan.
Sumber: jama





